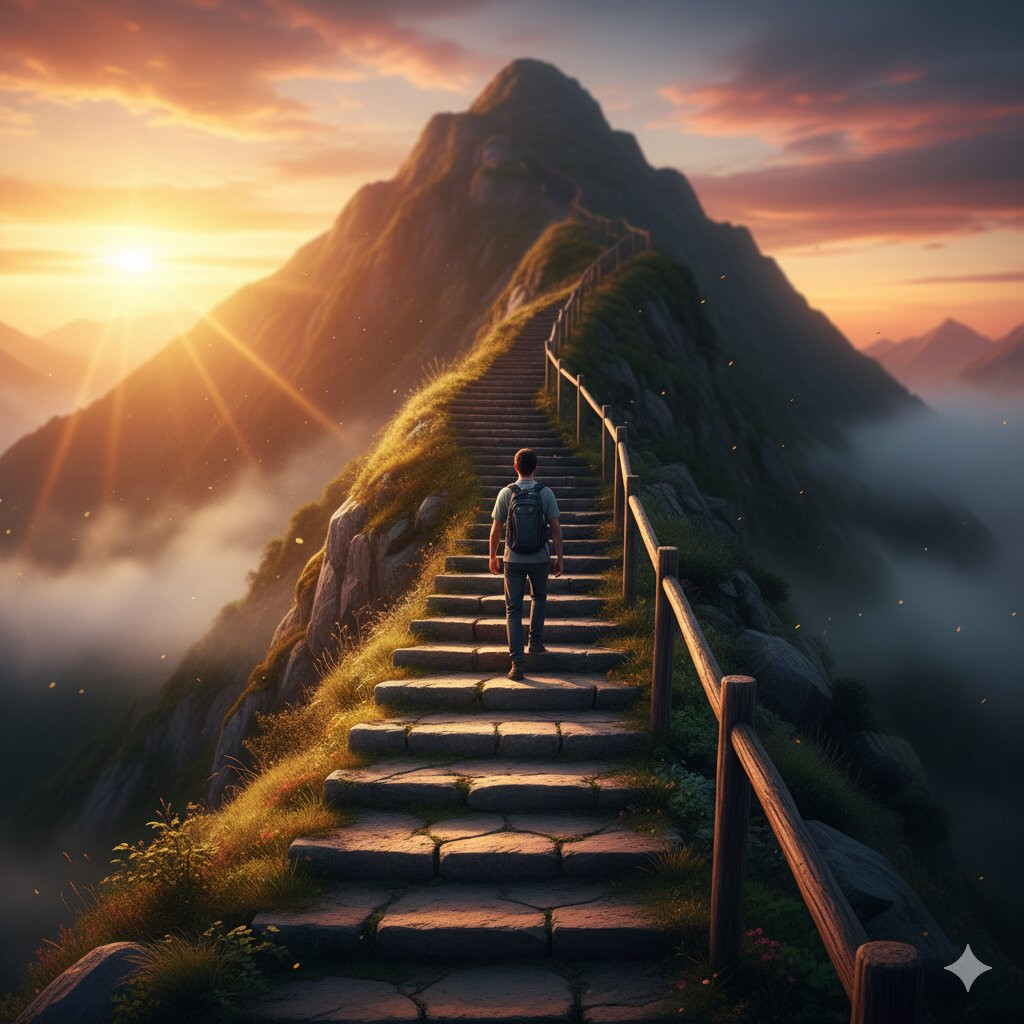Halaman 1 — Melatih Hati di Tengah Dunia Yang Tak Pernah Stabil
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Kita tumbuh dengan cerita bahwa bahagia adalah hasil keberuntungan. Katanya, kalau nanti sukses, baru bisa tenang. Kalau sudah punya rumah, baru bisa lega. Kalau pasangan sempurna datang, barulah hidup terasa lengkap. Tanpa sadar, kita menaruh kebahagiaan di masa depan — seolah ia adalah hadiah yang menunggu giliran.
Namun realitas berkata lain. Ada orang yang semua impiannya tercapai, tapi tetap merasa kosong. Ada pula yang hidup sederhana, namun wajahnya teduh dan hatinya stabil. Jika kebahagiaan adalah keberuntungan, seharusnya ia mengikuti kekayaan dan fasilitas. Tapi kenyataannya, ia lebih sering tinggal pada hati yang terlatih.
Dalam pendekatan psikologi positif modern, kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai peristiwa, melainkan sebagai kompetensi psikologis. Berbagai penelitian pustaka dan observasi lapangan menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti uang dan status hanya memberi dampak sementara. Setelah fase adaptasi, manusia kembali pada “baseline” emosionalnya. Artinya, tanpa pelatihan batin, sebanyak apa pun keberuntungan datang, ia tidak akan bertahan lama.
Al-Qur’an telah lebih dulu mengajarkan bahwa sumber ketenangan bukanlah situasi, melainkan kondisi hati. Kebahagiaan bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi bagaimana hati memaknai.
Alladzīna āmanū wa tathma’innu qulūbuhum bidzikrillāh. Alā bidzikrillāhi tathma’innul-qulūb.
Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra‘d [13]: 28)
Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan adalah hasil proses internal. Hati yang dilatih mengingat, bersyukur, dan menerima takdir akan stabil dalam perubahan. Sebaliknya, hati yang tidak terlatih akan mudah runtuh oleh sedikit kekecewaan.
‘Ajaban li amril-mu’min, inna amrahu kullahu lahu khair.
Artinya: “Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena seluruh urusannya adalah baik baginya.” (HR. Muslim)
Hadis ini bukan sekadar motivasi, tetapi prinsip mentalitas. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur; jika mendapat ujian, ia bersabar. Dua-duanya menguatkan jiwanya. Inilah bentuk kebahagiaan yang berbasis kemampuan, bukan keberuntungan.
Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi “kapan saya beruntung?”, tetapi “sudahkah saya melatih hati saya?”. Sebab bahagia adalah skill — dan seperti skill lainnya, ia perlu kesadaran, latihan, dan konsistensi.
Halaman berikut (2/10):
“Ilmu Kebahagiaan: Antara Psikologi dan Wahyu.”
Kita akan membahas bagaimana riset ilmiah dan ajaran spiritual bertemu dalam menjelaskan cara kerja kebahagiaan manusia.