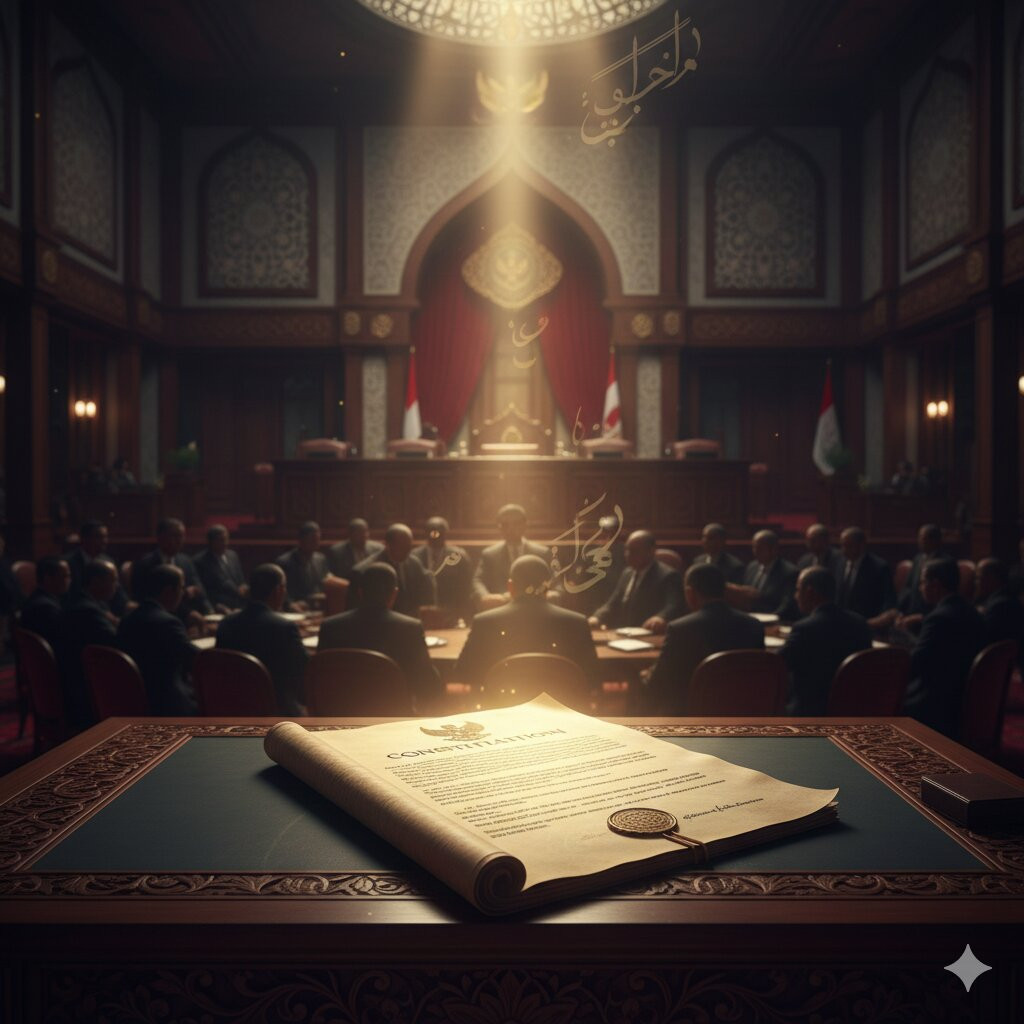Halaman 1 — Antara Ideal dan Realitas Wajah Lain Demokrasi Kita
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Ada satu lembaga negara yang secara konstitusional lahir dengan semangat besar, tetapi dalam praktik politik sering terlihat terlalu tenang di tengah badai. Ia tidak gaduh, tidak dominan dalam headline media, dan jarang menjadi pusat kontroversi legislasi. Namun justru di situlah pertanyaannya: apakah ketenangan itu tanda kedewasaan, atau justru tanda keterbatasan? Inilah ironi yang mengiringi keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Artikel ini disusun menggunakan pendekatan penelitian pustaka dengan menelaah amandemen UUD 1945, dinamika pembentukan DPD pasca-reformasi, serta praktik legislasi dua dekade terakhir. Data sekunder berupa dokumen resmi, risalah sidang, dan kajian akademik menjadi dasar analisis untuk memahami posisi DPD secara objektif. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga membaca realitas politik yang menyertainya.
Secara normatif, DPD dirancang sebagai representasi daerah dalam sistem bikameral. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi membutuhkan kanal aspirasi yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh partai politik. DPD hadir sebagai jawaban atas sentralisasi kekuasaan yang pernah menguat pada masa lalu. Ia diharapkan menjadi jembatan antara pusat dan daerah, serta penjaga kepentingan regional dalam setiap pembentukan undang-undang.
Namun politik bukan sekadar desain ideal. Politik adalah arena kekuatan. Dalam praktik legislasi, DPD memang dapat mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya. Akan tetapi, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden. Di sinilah muncul kesan bahwa DPD terlalu sopan di tengah politik yang keras — hadir, tetapi tidak menentukan.
Jika kita menelaah lebih dalam, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah DPD lemah, melainkan apakah sistem memang tidak memberikan ruang penuh untuknya menjadi kuat. Dalam arsitektur kekuasaan, setiap kewenangan adalah desain sadar. Ketika kewenangan itu dibatasi, maka pembatasan tersebut adalah pilihan politik. Maka, memahami DPD berarti membaca ulang arah demokrasi Indonesia: apakah kita benar-benar menginginkan representasi daerah yang kuat, atau hanya simboliknya saja?
Innal-lāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsān...
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Naḥl [16]: 90)
Prinsip keadilan dalam ayat tersebut relevan dengan desain kelembagaan negara. Keadilan politik tidak hanya soal pemilu yang rutin, tetapi juga soal distribusi kewenangan yang proporsional. Jika daerah diberi suara, maka suara itu seharusnya memiliki daya pengaruh, bukan sekadar formalitas prosedural.
Maka halaman pertama ini bukan untuk menyimpulkan, tetapi untuk menggugah: apakah DPD memang terlalu sopan untuk politik keras, atau justru kita yang belum berani memberi ruang agar ia menjadi aktor sejajar dalam demokrasi?
Halaman berikut (2/10): “Jejak Konstitusional: Mengapa DPD Dilahirkan?”
Kita akan menelusuri sejarah amandemen UUD 1945 dan memahami motif politik di balik pembentukan DPD.