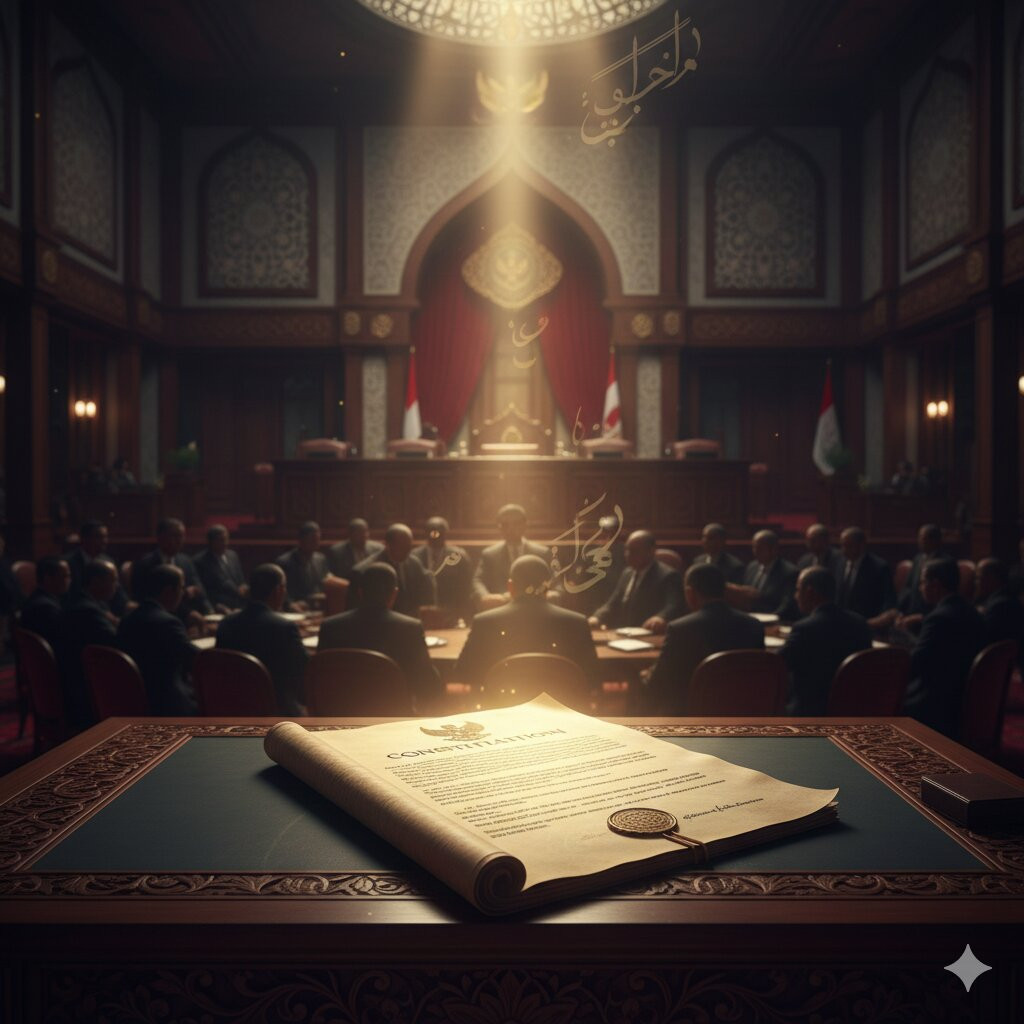Halaman 1 — Suara yang Sepi Ketika Wakil Daerah Tak Dibela
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Dalam setiap pemilu, rakyat daerah dengan antusias memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Nama-nama kandidat dikenal, baliho terpasang di jalan-jalan, janji penguatan aspirasi daerah dikumandangkan. Namun ketika kewenangan DPD diperdebatkan, ketika posisinya dianggap lemah, atau ketika wacana penguatannya muncul di ruang publik, suara pembelaan dari rakyat daerah justru terdengar minim. Mengapa lembaga yang secara teoritis mewakili kepentingan daerah justru jarang dibela oleh masyarakat daerah itu sendiri?
Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka dengan menelaah literatur hukum tata negara, dinamika politik pasca-reformasi, serta pola partisipasi publik dalam isu kelembagaan. Analisis juga mempertimbangkan realitas sosial-politik di daerah, termasuk relasi antara masyarakat, partai politik, dan wakil terpilih. Pertanyaan utamanya sederhana tetapi fundamental: apakah rakyat tidak peduli pada DPD, atau mereka tidak merasa dampaknya?
Secara konstitusional, DPD dibentuk untuk mewakili daerah dalam sistem legislatif nasional. Ia hadir sebagai kanal aspirasi non-partisan, berbeda dari DPR yang berbasis partai politik. Dalam teori demokrasi, representasi teritorial seperti ini sangat penting untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Namun legitimasi sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh teks konstitusi, melainkan oleh persepsi publik terhadap efektivitasnya.
Banyak masyarakat daerah lebih mengenal anggota DPR dari partai politik tertentu dibanding anggota DPD dari provinsinya sendiri. Isu-isu nasional yang ramai di media lebih sering dikaitkan dengan DPR. Ketika terjadi perdebatan undang-undang besar, publik cenderung memusatkan perhatian pada DPR dan pemerintah. DPD jarang menjadi sorotan utama. Akibatnya, kedekatan emosional antara rakyat daerah dan lembaga ini tidak terbentuk secara kuat.
Di sisi lain, masyarakat sering mengukur wakilnya berdasarkan hasil konkret: proyek pembangunan, alokasi anggaran, atau kebijakan yang langsung terasa. Jika kontribusi DPD dalam proses legislasi tidak terlihat secara kasat mata, maka wajar jika publik kesulitan merasakan urgensi untuk membelanya. Dalam politik, persepsi efektivitas sering kali lebih kuat daripada legitimasi normatif.
Wa lā talbisul-ḥaqqa bil-bāṭili wa taktumul-ḥaqqa wa antum ta‘lamūn.
Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)
Ayat tersebut mengingatkan pentingnya kejelasan peran dan transparansi. Jika peran DPD tidak dipahami secara jelas oleh publik, maka kebenaran tentang fungsinya mudah tertutup oleh dominasi wacana politik lain. Ketidaktahuan kolektif dapat melahirkan sikap apatis, bukan karena rakyat menolak, tetapi karena mereka tidak melihat urgensinya.
Maka halaman pertama ini bukan untuk menyalahkan rakyat daerah, melainkan untuk menggugah kesadaran: apakah jarangnya pembelaan terhadap DPD disebabkan oleh kurangnya kinerja, kurangnya kewenangan, atau kurangnya komunikasi politik? Pertanyaan ini akan kita telusuri lebih dalam pada halaman-halaman berikutnya.
Halaman berikut (2/10): “Legitimasi Tanpa Kedekatan Emosional.”
Kita akan membahas hubungan psikologis antara rakyat daerah dan wakilnya di DPD.