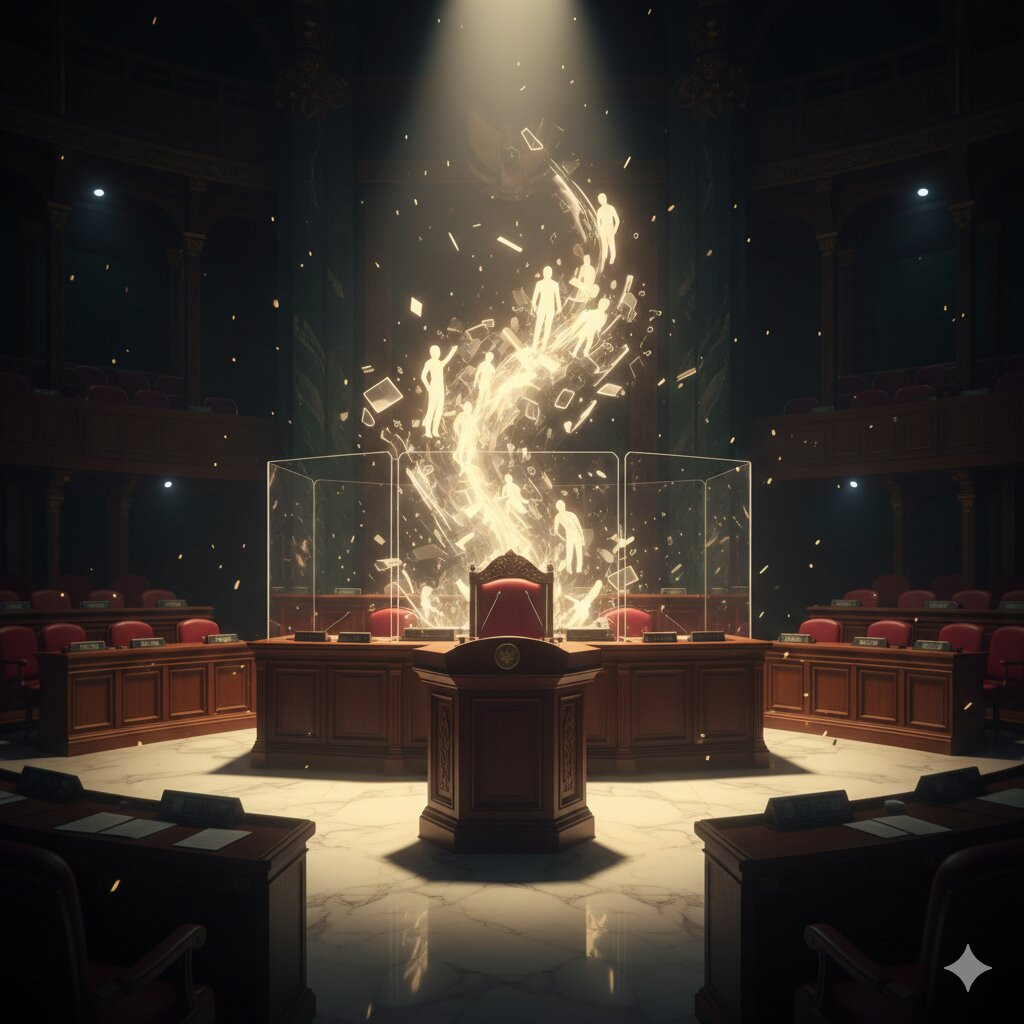
Halaman 1 — Ketika Kritik Dianggap Ancaman Membaca Sikap Defensif Lembaga Perwakilan
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Dalam teori demokrasi, kritik adalah oksigen bagi kekuasaan. Tanpa kritik, kekuasaan mudah membeku dalam zona nyaman, kehilangan sensitivitas terhadap suara rakyat. Namun dalam praktik politik Indonesia, muncul fenomena yang berulang: setiap kali DPR dikritik—baik terkait pembahasan undang-undang, anggaran, maupun sikap politik—respons yang muncul sering kali bersifat defensif. Kritik dianggap sebagai serangan, bukan sebagai masukan. Pertanyaannya menjadi relevan: mengapa lembaga yang seharusnya mewakili rakyat justru kerap menunjukkan sikap defensif ketika rakyat bersuara?
Dalam pendekatan penelitian pustaka, demokrasi deliberatif menempatkan kritik sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan. Jürgen Habermas menyebut ruang publik sebagai arena diskursus rasional, di mana argumentasi diuji melalui dialog terbuka. Dalam kerangka ini, lembaga legislatif seharusnya menjadi ruang paling terbuka terhadap evaluasi publik. Namun realitas menunjukkan adanya ketegangan antara ekspektasi normatif dan praktik komunikasi politik yang terjadi.
Secara psikologis, sikap defensif sering muncul ketika suatu institusi merasa legitimasi atau kewibawaannya terancam. Kritik publik, terutama yang viral di media sosial, dapat dipersepsikan sebagai delegitimasi. Dalam konteks DPR, kritik yang keras kadang dibalas dengan pernyataan klarifikasi yang menekankan prosedur formal, bukan substansi kritik itu sendiri. Alih-alih membuka ruang dialog, respons tersebut justru memperlebar jarak antara lembaga dan masyarakat.
Dalam perspektif etika Islam, kritik bukanlah permusuhan, melainkan bentuk nasihat. Konsep amar ma’ruf nahi munkar mengajarkan pentingnya saling mengingatkan demi kebaikan bersama. Kritik yang konstruktif seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap amanah publik.
Watā‘āwanū ‘alal-birri wat-taqwā wa lā ta‘āwanū ‘alal-ithmi wal-‘udwān.
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Mā’idah [5]: 2)
Ayat tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam kebaikan. Kritik terhadap kebijakan publik seharusnya diposisikan sebagai bagian dari kerja kolektif memperbaiki negara. Jika kritik selalu dimaknai sebagai ancaman, maka ruang perbaikan akan menyempit. Demokrasi yang matang justru ditandai oleh kemampuan menerima kritik tanpa kehilangan wibawa.
Artikel ini akan menggunakan pendekatan ilmiah dengan mengkaji faktor struktural, psikologis, dan budaya politik yang melatarbelakangi sikap defensif DPR terhadap kritik. Apakah defensivitas tersebut lahir dari tekanan politik, persepsi ancaman legitimasi, atau budaya kekuasaan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap partisipasi publik? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar jurang antara rakyat dan wakilnya tidak semakin melebar.
Mengkritik DPR bukan berarti memusuhi negara. Sebaliknya, kritik adalah ekspresi kepedulian terhadap kualitas demokrasi. Jika lembaga perwakilan mampu mengelola kritik secara konstruktif, maka kepercayaan publik dapat diperkuat. Tetapi jika kritik terus diperlakukan sebagai ancaman, maka yang terancam bukan hanya citra lembaga, melainkan kesehatan demokrasi itu sendiri.
Halaman berikut (2/10): “Psikologi Kekuasaan: Mengapa Kritik Terasa Mengancam?”
Kita akan menelaah faktor psikologis dan sosiologis yang membentuk respons defensif dalam institusi politik.



